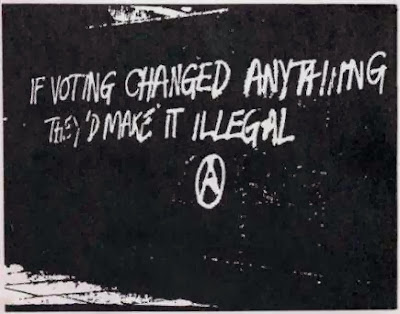 |
| hanya ada satu kata; kenthu! |
Dalam hidup, kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Baik dalam skala kecil nan sederhana, sampai skala besar nan kompleks. Pun dengan pemilu; karena berbicara soal pemilu, pastilah berbicara soal pilihan. Pemilu, adalah sebuah proses pemilihan seseorang untuk jabatan politik tertentu. Dan dalam proses pemilihan tersebut, seorang pemilih tentu dipengaruhi beberapa faktor, sehingga membuat si pemilih merasa perlu untuk turut menyumbangkan suara. Aurel Croissant, seorang profesor ilmu politik dari University of Heidelberg, mengatakan ada tiga faktor pendorong yang mempengaruhi seorang pemilih untuk terlibat dalam proses pemilu: fungsi keterwakilan, integrasi, serta kemampuan dan jaminan stabilitas seseorang untuk menjalankan jabatannya. Lalu pertanyaannya adalah: bagaimana jika faktor tersebut tak sanggup dipenuhi oleh sang calon empunya jabatan?"Voting for the lesser of two evils is still voting for evil. Next time, go all out and write in Lucifer on the ballot. ” ― Jarod Kintz, 99 Cents For Some Nonsense.
Kebanyakan pemilih di
Indonesia, tak mempermasalahkan apabila seorang calon tidak memlih faktor
pendorong kedua dan ketiga. Dalam The
Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, dijelaskan bahwa
masyarakat —khususnya di skala lokal— masih melihat faktor keterwakilan; entah ditinjau
dari aspek geografis, maupun —meminjam istilah Feith dan Castle— ikatan
emosional, sebagai salah satu faktor kuat yang membuat mereka turut menyumbang suara. Wajar, karena isu yang
dijual oleh para bakal calon ini cenderung lebih dekat dengan kepentingan
pemilih lokal. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan
kualitas pemilihan. Berbekal pendidikan politik yang baik, hal-hal yang dinilai
tidak relevan dengan jaminan mutu, kini tidak lagi menjadi jaminan faktor
pendorong. Integrasi dan kemampuan seseorang untuk menjalankan jabatan, kini
dipandang sebagai faktor utama yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Akan
tetapi, perlu diketahui juga bahwa tidak semua bakal calon yang terlibat dalam
proses pemilu, memiliki jaminan mutu tersebut. Dalam sebuah sistem kepemimpinan
yang menjunjung tinggi asas demokrasi, setiap individu dinilai memiliki
kesempatan yang sama untuk menduduki sebuah jabatan politik. Asalkan sanggup
memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, baik/buruk-nya jejak rekam sang
bakal calon, tentu menjadi pertimbangan nomor sekian.
Berangkat dari
kecemasan inilah, muncul gerakan masif yang mulai merambat dari skala lokal
menuju ke skala nasional. Gerakan ini disebut sebagai gerakan golongan putih
atau biasa disebut golput. Tidak memilih, adalah antitesa dari hiruk pikuk
pemilu. Namun sekalipun begitu, golput bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam
proses pemilu, karena pemilu di Indonesia —termasuk pilkada— menggunakan sistem
legitimasi formal, dan prinsip memilih sebagai sebuah voluntary voting. Sebagaimanapun tingginya angka golput, tidak akan
pernah membatalkan hasil pemilu. Meski secara substansif, tingginya angkat
golput ini merepresentasikan rendahnya legitimasi serta kepercayaan para pemilih
terhadap bakal calon, atau bahkan pemilu itu sendiri. Namun jika ingin
dicermati, gerakan golput sebenarnya memiliki kecenderungan membela hak pilih, hanya
saja hak pilihnya bukan untuk memilih partai tapi hak pilih untuk tidak
memilih.
Golput sendiri, hadir
bukan tanpa alasan. Golput merupakan bentuk perilaku memilih, yang
kecenderungannya ditentukan oleh pelbagai kajian teori. Kajian teori yang
paling relevan, mungkin melalui kajian teori sosiologis dan psikologis. Sebagaimana
pernah dikemukakan dalam jurnal National
Choice Theory terbitan Michigan University, perilaku memilih ini bukan
merupakan bentuk reaksi, bukan sebuah aksi. Seringkali, kalkulasi untung rugi
yang menjadi pertimbangan utama dalam gerakan ini.
Dalam hal ini, golput
—bisa juga disebut perilaku tidak memilih (non
voting behavior)—merupakan bentuk reaksi, atas sebuah fenomena dalam
pemilu yang dinilai akan menimbulkan kerugian. Penumpukan rasa kecewa dan
frustasi, tentu akan melahirkan krisis kepercayaan. Belum lagi, ditambah dengan
ketakutan akan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Situasi less democracy ini sebetulnya sudah
pernah digadang-gadang oleh Franklin D. Roosevelt: “Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared
to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education.”
Menurut hemat saya,
sedari awal golput memang tidak memiliki target untuk meng-ilegitimasi-kan pemerintahan hasil pemilu.
Saya yakin pula, bahwa mereka yang terlibat di gerakan ini sadar bahwa tidak
ada pengaruh yang terlalu signifikan yang bisa dicapai melalui golput. Namun
perlu diketahui juga, pada pemilu 1973, bukan tanpa tujuan Arief Budiman dan
kawan-kawannya mencetuskan gerakan golput. Kala itu, ia memilih gerakan ini sebagai
tandingan Golkar yang dianggap membelokkan cita-cita awal Orde Baru untuk
menciptakan pemerintahan yang demokratis. Apa yang dilakukan Arief, tendensinya
memang untuk memberikan pesan kepada pemerintah; bahwa ada gerakan moral yang
bergerilya di bawah sistem politik autokrasi yang penuh dengan pengebirian
kebebasan sipil, dan pemasungan aspirasi rakyat.
Salah satu putera terbaik
bangsa ini, Aburrahman Wahid, juga memilih jalur golput dalam pemilu Presiden
2004, sebagai bentuk protes atas kecurangan, pemihakan, manipulasi yang
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melanggar sejumlah
undang-undang (UU), UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, No.4/1997 tentang
Penyandang Cacat, No. 12/2003 tentang Pemilu Legislatif dan dua pelanggaran
terhadap UU No.23/2003 tentang Pemilu Presiden. Namun yang membedakan gerakan
Arief dengan Gus Dur adalah, Gus Dur memenuhi ketentuan undang-undang tentang hal
ini; tidak mengajak siapapun, melainkan melakukan tindakan yang merupakan
pilihan pribadinya. Sedangkan Arief
Budiman, bahkan sampai sekarang masih menyerukan ajakan golput dalam skala
nasional secara lantang.
Sekali lagi, tak ada yang bisa
mengelak bahwa tingginya angka golput memang merupakan representasi minimnya
legitimasi pemerintah, sehingga kedudukan dan kepemimpinan bakal calon masih
disangsikan oleh masyarakat. Namun rasanya, terus-menerus ‘melepas tangan’ dari
keikutsertaan pemilu hanya menjadi cerminan rasa skeptis yang tak berujung.
Apalagi, jika kemudian para pemilih yang menganut paham golput, hanya berpangku
tangan setelah gegap gempita pemilu usai. Tak ada realisasi lebih lanjut, dari
bentuk protes dan kekecewaan yang sebelumnya mereka gembar-gemborkan.
Maka dari itu —sebagai sebuah
gerakan moral— dalam kajian demokrasi hari
ini, rasa-rasanya paham golput tak lagi relevan. Jika dirasa ada sebuah sistem yang
keliru, bukankah lebih baik apabila kemudian ikut bergerak untuk membenahinya?
Bukan hanya menjadi komentator serta penonton yang simple minded, dengan selalu mempermasalahkan keadaan sekitar, tapi
kemudian tak pernah ikut serta dalam usaha menyelesaikan persoalan.
Kita hidup dalam sistem demokrasi.
Kita diberikan hak untuk turut memperbaiki sistem yang berlaku, tanpa perlu
membubarkan sistem yang sudah ada. Dan yang perlu diingat, sistem
demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memberikan ruang bagi koreksi,
termasuk kepada sistem itu sendiri. Tak perlu skeptis ketika jumpa demokrasi, hadapi saja
dengan santai —jangan terlalu serius—, karena seperti kata Goenawan Muhammad
dalam Catatan Pinggir 7, demokrasi
tak ayal seperti teater; ini bukan soal proses menemukan kebenaran, namun tentang
mengatasi serta menghadapi kesalahan.

Saya tidak dapat cukup berterima kasih kepada Dr EKPEN TEMPLE kerana telah membantu saya mengembalikan kegembiraan dan ketenangan dalam perkahwinan saya setelah banyak masalah yang hampir menyebabkan perceraian, alhamdulillah saya bermaksud Dr EKPEN TEMPLE pada waktu yang tepat. Hari ini saya dapat mengatakan kepada anda bahawa Dr EKPEN TEMPLE adalah jalan keluar untuk masalah itu dalam perkahwinan dan hubungan anda. Hubungi dia di (ekpentemple@gmail.com)
BalasHapus