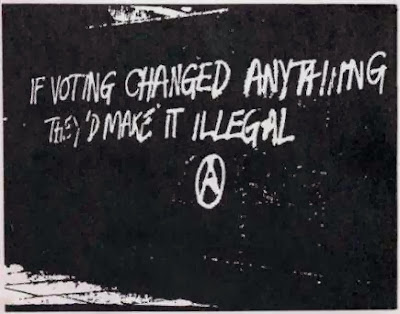.jpg) |
| Wis to Mas, percoyo aku. Enak anak. |
“…dulu
kanan dan kiri jalan ini
pohon-pohon asam besar melulu
saban lebaran dengan teman sekampung
jalan berombongan
ke taman sriwedari nonton gajah
banyak yang berubah kini
ada holland bakery
ada diskotik ada taksi
gajahnya juga sudah dipindah
loteng-loteng arsitektur cina
kepangkas jadi gedung tegak lurus…”
pohon-pohon asam besar melulu
saban lebaran dengan teman sekampung
jalan berombongan
ke taman sriwedari nonton gajah
banyak yang berubah kini
ada holland bakery
ada diskotik ada taksi
gajahnya juga sudah dipindah
loteng-loteng arsitektur cina
kepangkas jadi gedung tegak lurus…”
“Jalan Slamet Riyadi
Solo” — Wiji Thukul, Aku Ingin Jadi
Peluru (2000)
R
|
asa-rasanya, tak perlu
saya menjelaskan mengenai makna tersirat dari puisi di atas. Secara gamblang,
Thukul berbagi keluh tentang wajah kota kelahirannya yang kini telah berganti
rupa. Baginya, bahagia kini tak bisa ditebus dengan cara-cara sederhana.
Sebermula dari sudut kota yang menjadi tempatnya berbagi tawa bersama teman
sekampung, berganti menjadi tempat mewah; di mana tawa semringah berbanding
lurus dengan banyaknya gelontoran rupiah. Kegamangan seperti inilah, yang
mungkin saya rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Duapuluh satu tahun saya
hidup di Solo, selama itu pula saya menyaksikan kota ini makin gemar bersolek
—kalau tak ingin dikatakan berubah. Pangling? sudah barang tentu. Kecewa? Hmm,
nanti dulu.
**********************************
Kedua
orangtua saya adalah seorang perantau. Ibu saya adalah seorang Sunda tulen,
yang lahir dan tumbuh besar di Tasikmalaya. Sedangkan ayah saya, menghabiskan
masa kecil dan masa mudanya di Indramayu. Setelah menikah, mereka hijrah ke
Solo karena urusan pekerjaan. Saya lahir di tahun pertama setelah mereka
menginjakkan kaki di kota ini. Entah memang mbrojol
karena sudah direncanakan, atau karena mak-mbendhunduk
njedul di tengah-tengah kesibukan mereka di tanah perantauan. Yang saya
maksut dengan kesibukan, tentu ‘kesibukan’ di luar urusan pekerjaan. Maklum,
sebagai orang rantau—merangkap sebagai pasangan pengantin baru yang tak
memiliki kerabat juga sanak saudara, tentu kesibukan-di-luar-pekerjaan macam
apa yang saya maksut ini, sudah saling kita ketahui bersama. Yah, namanya juga
pengantin baru.
Akhirnya, saya lahir ke dunia. Meski tak memiliki
garis keturunan Jawa, atau dibesarkan dalam keluarga yang njawani banget, saya selalu memperkenalkan diri sebagai orang asli
Solo, setiap kali berkenalan dengan seseorang di luar kota. Beberapa orang
mungkin menyebutnya sebagai kebanggaan semu, tapi saya menyebutnya sebagai
identitas. Saya merasa senang saja, kalau bisa memperkenalkan kota kelahiran
saya kepada orang lain. Apalagi kalau kemudian mereka bertanya perihal seluk
beluk kota ini. Tanpa perlu diminta, seketika kemampuan saya untuk bercerita
mengenai kota Solo dari A-Z menjadi fasih; mungkin menyamai kemampuan berbicara
para gadis-gadis cantik berpakaian batik yang ada di iklan biro pariwisata.
Semakin hari, tentu pengalaman hidup saya semakin bertambah. Setelah melakukan pelbagai perjalanan, berulang kali singgah
ke tempat-tempat baru yang selama ini belum pernah dikunjungi, jumpa banyak
orang—dengan karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda pula, saya
belajar satu hal: yang saya dapatkan selama tinggal di Solo sampai sekarang,
mutlak soal kesederhanaan hidup. Ini, yang mendasari saya untuk memperkenalkan
Solo kepada khalayak. Bukan hanya soal destinasi wisata semata, lebih dari itu,
saya merasa ada nilai-nilai sosial di kota ini yang harus dipelajari oleh
setiap orang, bila ingin mencapai kesempurnaan hidup. Terdengar berlebihan?
Tunggu sampai kalian datang kota ini. Buktikan sendiri, Solo akan membuatmu
berulangkali jatuh cinta dengan cara yang sama.
Saya pertama kali jatuh cinta dengan kota ini, saat masih
berusia belasan. Mungkin saat menginjak bangku sekolah menengah pertama, saat
perlahan-lahan saya menyadari bahwa nikmat dunia juga bisa berasal dari harta,
dan…uhm — paras cantik wanita. Sosok
gadis cantik nan pendiam dari kelas sebelah, membuktikan bahwa magis Putri Solo
memang benar adanya. Saya ingat betul, gerak malu-malunya tatkala berpapasan
dengan saya di kantin. Hanya bisa tersipu, dan lirih membalas rayuan saya dengan
suara medhok-nya yang kental dan
khas. Parasnya memang cantik, tapi saya yakin bedak dan berbagai macam riasan
aneh-aneh itu hanya sesekali bersarang di wajahnya. Maklum saja, waktu itu bagi
kami —siswa SMP, perkembangan harga Lembar Kerja Siswa (LKS) di belakang
Sriwedari lebih menarik disimak, dibanding naik-turun harga kosmetik di gerai
Matahari. Bandingkan saja, dengan tampilan siswi SMP di Ibu Kota. Tampil jauh
lebih matang melebihi usia aslinya. Nampaknya, harus ada ahli bahasa yang
mencatut definisi ‘menyerupai ibu-ibu atau tante-tante’ dari kata ‘cantik’, di Kamus Besar Bahasa Indonesia
yang beredar di sekolah-sekolah Ibu Kota. Singkat kata, kalau ingin membuat
daftar alasan untuk jatuh cinta dengan Solo, jangan lupa sertakan Puteri Solo
ke dalam posisi tiga besar.
Beranjak remaja, tentu lingkup bermain saya semakin luas.
Yang awalnya hanya berkeliaran di berbagai rental Playstation, pematang sawah,
atau lapangan sepakbola, kini mulai beralih ke pusat perbelanjaan atau kafe. Namun uniknya, dari dulu sampai sekarang saya tak pernah menjadikan kafe atau pusat
perbelanjaan sebagai alternatif utama ketika ada seorang kawan bertanya, “Cah, nongkrong neng ndi ki?”. Selalu,
saya mengajukan tawaran untuk nongkrong di wedangan
saja, toh bagi saya nongkrong di mana saja tak pernah jadi masalah, selama
teman nongkrongnya adalah orang-orang yang menyenangkan. Tak ayal, di kota ini
saya punya beberapa tempat wedangan yang
menjadi langganan. Mulai dari yang di pinggir jalan, di emperan toko, sampai
halaman rumah yang disulap menjadi tempat wedangan; lengkap dengan angkringan beserta lincak yang menjadi fasilitas para
pengunjungnya untuk betah berlama-lama teng-teng-cit/tenguk
tenguk crito, berleha-leha sembari berbagi cerita.
 |
| Teng-teng cit. Tenguk-tenguk sambi cerito |
Nongkrong sembari beralas tikar di pinggir jalan, atau
duduk di atas lincak—bangku panjang
yang terbuat dari bambu, bagi sebagian orang mungkin terkesan biasa saja atau
bahkan dianggap sebagai alternatif tongkrongan masyarakat kelas bawah. Tapi
percayalah, bukan tanpa alasan kenapa saya selalu menjadikan wedangan sebagai alternatif tongkrongan
utama. Di berbagai sudut kampung di Solo wedangan
dianggap sebagai sarana gebyar temu keberagaman, sekaligus menjadi fasilitas
warga sekitar untuk bersosialisasi. Bagaimana tidak, di wedangan, gelar profesor, haji, dokter, copet, preman, karyawan,
mahasiswa, pedagang, semuanya lebur. Semua seragam: kaos polos —kadang ditutup
dengan jaket hadiah dari dealer motor,
sarung apek yang diselempangkan selayaknya pertanda gelar Putra-Putri Solo, dan
celana kolor; semua berkumpul, tunduk dalam kuasa aneka ragam sate penuh
kolesterol.
Sering saya bersama beberapa teman berkeliling ke perkampungan-perkampungan, hanya
untuk mencari suasana wedangan baru,
sekaligus mencari obrolan-obrolan menarik dengan sang bakul. Uniknya, kemampuan seorang bakul wedangan bukan hanya ditentukan dari bagaimana dia menyajikan
hidangan, meracik teh, atau menyuguhkan aneka ragam santapan yang nikmat, tapi
juga dituntut untuk bisa menjalin komunikasi dengan para pembeli yang tak
pernah kehabisan bahan cerita. Sang bakul,
harus tahu kapan harus diam, kapan harus memulai/mengakhiri bahan obrolan, nyamber di antara sebuah percakapan,
atau paling tidak, punya kemampuan untuk meng-ho’oh-ho’oh-i setiap ucapan pembeli, tanpa terkesan menyakiti. Di wedangan, semua topik tak
pernah dirasa terlalu basi untuk dibicarakan. Mulai dari taktik sepakbola
timnas, gosip selebritis tanah air, rahasia negara, gonjang-ganjing prahara
rumah tangga tetangga sebelah, besaran biaya SPP anak yang semakin mencekik,
kiat-kiat menjadi jawara saat melakoni hubungan suami-istri, sampai jokes om-om yang membahas agama,
politik, juga selangkangan. Saya ingat betul, seorang kawan dari luar kota yang
menolak saya ajak ke restoran cepat saji untuk makan malam, dan memilih untuk
makan di wedangan, karena ingin
mencoba sendiri bagaimana sensasi makan sembari guyub dengan sekitar.
Bagi
saya, wedangan di kota Solo bukan
merupakan antitesis dari simbol-simbol kemakmuran yang sering ditampilkan kaum
borjuis saat nongkrong di kafe kelas menengah ke atas. Wedangan adalah budaya, yang merepresentasikan perangai warga kota
Solo: guyub, nyengkuyung, dan
sederhana —bahasa halus dari irit, kalau bukan berkantung tipis. Tidak, saya
bercanda. Sebetulnya, wedangan adalah
bentuk perlawanan atas ulah para kapitalis dan sosialis yang telah menggerogoti
kestabilan ekonomi negeri in. Ini merupakan gelanggang bagi kami —para kaum
buruh, untuk bertukar pikiran dan gagasan dalam rangka memajukan kesejahteraan wong cilik. Tidak, saya bercanda lagi.
Maaf.
Sebetulnya,
kesederhanaan di Solo juga bisa diartikan secara harafiah. Biaya SPP di UNS
—satu-satunya perguruan tinggi negeri di kota ini, termasuk biaya SPP yang
paling murah di antara perguruan tinggi se-Indonesia. Biaya hidup di Solo,
masih tergolong murah. Sebagai contoh, Anda masih bisa mendapatkan banyak opsi
tempat makan murah nikmat —selain wedangan,
hanya berbekal selembar rupiah bergambar Tuanku Imam Bonjol, atau paling banter
Sultan Mahmud Badaruddin.
**********************************
Beberapa
tahun belakangan, Solo bersolek diri. Semenjak Jokowi menjadi orang nomor satu
di kota ini, banyak perbaikan dan pembenahan di sana-sini. Perbaikan birokrasi,
serta revitalisasi ekonomi, kebudayaan, dan pariwisata, menjadi fokus utama
pria berbadan ceking ini. Walhasil, Solo kini menjadi kota metropolis. Event berskala nasional maupun
internasional kini semakin sering singgah kemari, pusat perbelanjaan berskala
besar yang awal mula jumlahnya bisa dihitung dengan jari, kini semakin banyak
dan bervariasi. Kafe atau tempat nongkrong yang sudah tenar di luar kota, kini
mulai melebarkan jangkauan ke kota Bengawan. Jika dirasa mengejutkan, tunggu
sampai Anda mengetahui fakta ini: sejak 2012 hingga Juni 2013, Pemerintah kota
sudah menerbitkan izin mendirikan bangunan kepada 21 hotel. Iya, 21. Anda tidak
sedang salah, baca, atau saya sedang melebih-lebihkan jumlah ini agar terkesan
dramatis, memang jumlah itulah yang baru saja diterbitkan izinnya oleh
pemerintah.
Pada
periode itu, kursi pemerintahan tertinggi memang tak lagi dijabat Jokowi,
melainkan oleh Rudi, wakilnya yang setia menemani selama hampir dua periode
masa jabatan. Namun, Jokowi lah yang berperan untuk kembali menghidupkan geliat
ekonomi dan pariwisata kota Solo yang sempat tertunduk lesu. Ia yang
‘mendirikan’ pilar-pilar ini, agar kemudian bisa diteruskan oleh siapapun yang
menjabat sebagai orang nomor satu di Solo. Tanpa mengecilkan peran Rudi, serta
pejabat-pejabat terkait lainnya, mungkin kalau kata orang Jawa, pekerjaan ini gari nuthukne, atau tinggal meneruskan.
Jokowi seakan menanam bibit unggul, yang mungkin siap berbuah kapan saja, dan
siap dipetik oleh siapa saja.
Hingar
bingar prestasi Jokowi, membuat gaung namanya menggema di seantero Nusantara.
Prestasinya semasa menjabat di kota Solo pula, yang membuatnya dilirik sebagai
pengisi jabatan orang nomor satu di Ibu Kota. Kalau boleh jujur, pada awalnya
saya sempat kecewa dengan keputusan ini. Ego saya berkata, orang seperti Jokowi
ini terlalu ‘suci’ untuk ditugaskan dalam benam lumpur kotor Jakarta, pikir
saya, biarkan saja kota itu diurus oleh orang lain, asal jangan Jokowi. Tapi
akhirnya saya berpikir, saya tak boleh egois. Salah satu putera terbaik bangsa
itu, bukan milik saya —atau rakyat Solo semata. Kalau memang hadirnya bisa
mengubah Ibu Kota negeri ini menjadi lebih baik, saya rasa biarkan saja menjadi
demikian. Bagi kami, warga Solo, melepas kepergian Jokowi ini bukan hanya soal
mampu, tapi lebih ke soal mau. Dan pada akhirnya, mau tidak mau, mampu tidak
mampu, harus mau juga mampu
Kembali
menyoal Solo. Geliat kota ini tak terhenti hanya karena Jokowi pergi. Seperti
yang sudah saya singgung sebelumnya, muncul banyak potensi yang menanti Solo
untuk menjadi lebih maju. Tapi sebagaimana puisi “Jalan Slamet Riyadi Solo” gubahan Thukul, saya
juga memiliki kegamangan akan konsekuensi yang harus ditebus, tatkala Solo
mulai bersiap untuk menjadi kota maju. Saya takut, bianglala yang menghiasi
kota ini nantinya akan menjadi nirwana pura-pura; di mana bahagia, rasa senang,
dan kebanggaan yang ada di dalamnya hanyalah semu belaka. Kota ini hanya nampak
istimewa dari luarnya saja, tapi di dalamnya ternyata banyak menyimpan luka yang tak nampak. Naudzubillah.
Tempo
hari, teman dekat saya berkata: “Wah, enak nih ada gerai X di Solo. Sekarang
kalau mau beli ini-itu, ndak usah
pergi ke luar kota. Praktis.” Sejurus kemudian, ia menambahkan, “Kalau ada
kerabat atau saudara dari luar kota yang mau liburan di sini, kita juga punya
banyak opsi tempat menginap nih sekarang. Ndak
melulu di hotel itu-itu saja.” Saya terdiam, ada benarnya juga perkataan
teman saya ini. Di luar segala puja-puji untuk kota ini, dulu saya selalu
kenyang dengan gurauan sarkas macam “Ah, di Solo memang ada?”, “Lho, kamu kan
di Solo, mana tahu soal beginian,” atau “Solo kan cuma itu-itu saja,” dari
kawan-kawan saya yang ada di luar kota. Mau tidak mau, harus diakui bahwa
stigma konservatif, kolot, terbelakang, tertinggal, memang sempat melekat pada
kota Solo. Tapi dengan hadirnya pelbagai fasilitas dan pembangunan di
sana-sini, sedikit demi sedikit stigma itu mulai tergerus. Akan tetapi
pertanyaannya adalah: apakah memang harus seperti itu, untuk membuktikan bahwa
kita ini adalah kota maju?
“Ndak gitu, Nyuk. Terus kalau gitu, bedanya kita sama kota-kota besar yang
saban hari kamu cela itu sekarang apa? Sudah sama semua sekarang. Ngopi di
tempat mahal, renang di hotel mahal, beli baju sampai menghabiskan gaji bulanan.
Ndak pernah tahu penemuan yang
namanya kopi sachet, blumbang, sama klithikan po? Ha?” ujar saya menanggapi
perkataan teman saya tadi.
“Yo ngene ki, sing marai kutha Solo ora ndang maju. Kamu itu
konservatif, yang dibahas cuma sentimen masa lalu thok til. Seakan ndak mau
terbuka sama masa depan. Yen enek kanca
dolan mrene, sing mbok duduhne mung reca Gladhag, sega liwet karo wayang Sriwedari
tok,” balas teman saya.
“Lho, memang itu
identitas kita kan?”
“Yo memang pancen kui identitas kita, tapi bukan berarti kita itu mandheg di situ tok. Kalau ada tawaran
untuk menjadi maju, ya diambil to ya. Eman
yen ora dijipuk. Solo kui berpotensi.”
Saya kembali terdiam.
Saya, sang pegiat wedangan, seakan
ditampar dengan kalimat: “Kamu itu konservatif, yang dibahas cuma sentimen masa
lalu thok til. Seakan ndak mau terbuka sama masa depan. Solo kui berpotensi, eman yen ora
dijipuk.” Bukan tanpa alasan, saya skeptis akan perubahan yang ada di kota
Solo. Saya hanya tidak ingin, elemen-elemen masyarakat di kota Solo memunculkan
gerakan Jogja Ora Didol jilid 2. Pedih rasanya, jika melihat kota ini dianggap
melakukan eksploitasi potensi yang ujung-ujungnya hanya dianggap memberikan
keuntungan tertentu bagi golongan tertentu pula.
Tapi di satu sisi, saya
juga tak ingin terjebak pada sentimen masa lalu semata. Kota ini harus beranjak
dewasa. Tapi tentu saja, tanpa melupakan akar rumput kota ini sebagaimana
mestinya. Dan yang paling penting, melibatkan masyarakat sebagai elemen
terpenting dalam pembangunan kota ini. Bisa?
**********************************
 |
| "Aku rindu harga tiket bis tingkat yang dulu," remaja 90-an Solo |
“Lulusan
sini banyak yang ditarik kerja di hotel-hotel baru itu, Mas. Dulu, banyak yang
lari ke luar kota, paling banyak Jogja, buat daftar cari kerja yang sesuai
dengan bidang kami. Alhamdulillah, sekarang
banyak hotel di sini. Sedikit banyak, meyakinkan kami kalau kami tidak salah
pilih jurusan,” ujar dia sambil tersenyum-cantik-minta-disayang. Betul saja
gumam saya. Sebetulnya hal-hal semacam ini adalah potensi —seperti kata teman
saya sebelumnya. Hanya saja, tergantung pada kita; ingin menjadikan ini sebagai
sarana menuju maju, atau menjadikannya belenggu menuju maju.
Perlahan
saya yakin, bahwa kota ini bisa menjadi maju tanpa menangggalkan aspek-aspek
terdahulu. Saya masih menyimpan keyakinan baik pada pemerintah, bahwa mereka
tak akan dengan mudahnya menggadaikan identitas kota ini hanya demi kepentingan
pribadi. Di tengah ke-skeptis-an saya akan kelestarian identitas kota ini,
rasanya selalu ada alasan untuk membuat saya kembali menjadi optimis. Mulai
dari antrian penumpang Batik Trans Solo, tawa anak-anak TK saat menaiki Bus
Tingkat Werkudara, senyum sapa alumni sekolah perhotelan saat saya mendatangi grand opening hotel baru, gegap gempita
segerombolan kolektif panas penggagas Rock In Solo, dan yang hebat baru-baru
ini: ucapan terima kasih dari petugas parkir yang mengenakan lurik berserta
blangkon, saat memberi uang kembalian. Saya rasa, optimisme itu masih ada.
Pada
akhirnya, kita hanya bisa berharap pemerintah dan segala aspek terkait untuk
tetap bekerja menggunakan hati nurani sebagai rujukan utama dalam setiap
pengambilan keputusan, serta berperan serta untuk memantau dan menjaga mereka
agar tetap pada lintasan, demi terciptanya cita-cita Solo yang maju juga
berbudaya. Klise dan terdengar seperti kalimat kesimpulan yang dibacakan oleh
moderator seminar politik yang (pura-pura) dihadiri mahasiswa (demi kepentingan
nilai dan absensi) sebuah universitas ternama; tapi memang benar adanya.
Saya
berharap, Solo bersolek dengan filosofi bedak dingin. Tetap bisa membuat
pemakainya tampil cantik dan menawan, namun dengan racikan tradisional yang tak
kalah menawan dibandingkan bedak modern yang hanya bisa ditembus dengan
beberapa lembar uang seratus ribuan. Sekali lagi, karena kota ini terlalu
berharga. Kota yang telah mengajarkan saya, tentang bagaimana menjaga
kesederhanaan dalam sebuah kemegahan. Lebih dari sekedar kota, bagi saya, Solo
adalah sekolah kehidupan.